Dalam
masa yang sangat panjang, jatuhnya kekuatan umat islam tidak dapat dipungkiri. Dunia
islam meradang akibat kolonialisme dan penyakit al-wahn dalam tubuh umat
islam sendiri. Saat dimana umat islam telah kehilangan jatidiri dan ruh mereka
dalam agama. Salah satu diantara penyebabnya adalah kiris ilmu pengetahuan. Meski
telah berulang kali digagas dan digulirkan, wacana ilmu pengasuhan ilmu dalam
kerangka konsep keilmuwan islam masih mengalami hambatan yang cukup berat.
Abu
Hasan Ali an-Nadwy, mengungkapkan kondisi itu. Bahwa dunia islam telah menyerah
dan mundur dari kepemimpinan dunia semenjak beberapa abad lamanya. Dunia islam
menjadi pengekor peradaban Barat. Bahkan hingga masalah tafsir, Hadits, dan
Fikih. Orang-orang Orientalis menjadi pembimbing dalam studi, penelitian dan
penulisan karya-karya ilmiah mereka. Akhirnya, persoalan hukum, pemikiran,
teori-teori ilmiah dan historis semuanya bersandar pada Barat.[1]
 |
| Abu Hasan ali an-Nadwy |
Ia
melanjutkan, bahwa para pemikir Islam di belahan dunia Timur tidak berdaya
membendung peradaban Barat dan tidak punya nyali untuk berdiri
berhadap-hadapan. Tidak punya kapasitas ilmiah dan intelektual untuk
melancarkan kritik, dan berani untuk menyatakan kemandirian intelektual. Di
saat yang sama, banyak yang telah mengalami cultural shock. Menganggap
bahwa peradaban Barat adalah akhir dan puncak peradaban tertinggi manusia
sepanjang sejarah. Padahal, telah disebutkan dalam beberapa tulisan sebelumnya,
bagaimana kerusakan yang timbul dari peradaban Barat. Dalam pengantar bukunya,
Marvin Perry mengungkapkan hal tersebut dengan lugas dan bernas, “Barat telah
menempa peralatan nalar yang memungkinkan pemahaman rasional atas alam
jasmaniah dan kebudayaan manusia, menyusun ide kemerdekaan politis, mengakui
nilai instrinsik. Tetapi Barat Modern meskipun telah membongkar seluk-beluk
misteri-misteri alam, kurang berhasil dalam menemukan berbagai solusi bagi
penyakit-penyakit sosial dan konflik di antara bangsa-bangsa. Ilmu, prestasi
besar intelek Barat, meskipun memperbaiki kondisi-kondisi kehidupan, juga telah
menghasilkan senjata-senjata perusak massal. Meskipun Barat adalah pelopor
dalam melindungi hak-hak asasi manusia, ia juga telah menghasilkan rezim-rezim
totaliter yang telah menginjak-injak kebebasan idividu dan martabat manusia.
Dan meskipun Barat telah memperlihatkan tekad kesetaraan manusia, ia juga telah
mempraktikkan rasisme yang brutal”.[2] Sebuah
ironi dan tragedi ditayangkan Barat dalam panggung sejarah manusia.
R.
D. K. Herman dalam tulisannya di jurnal Sustain Sci, yang berjudul Traditional
knowledge in a time of crisis: climate change, culture and communication membenarkan
hal tersebut, bahwa The disenchantment of the world and the apotheosis of
reason work together in the separation of humanity from integration with nature,
and with human nature. With the physical world thus set apart, it then became
the object of control[3].
(Penghilangan pesona alam dan pendewaan akal bekerja sama dalam
memisahkan kemanusiaan dari integrasinya bersama alam, dan dari sifat dasar
manusia itu sendiri. Dengan pemisahan dunia fisik demikian, menyebabkan alam
menjadi objek pengendalian.) Sehingga diperlukan rekonstruksi paradigma yang
dibangun di atas logika kapitalisme industri kepada paradigma yang mengintegrasi
kembali alam ke dalam nilai kemanusiaan. (This exhortation that nature can
and should be transformed through technology for the good of humanity is the
logic of industrial capitalism and has not been successfully challenged up to
the present time. The progression from the disenchantment of the world, to the
split between huma nity and nature, to the exhortation to dominate nature with
technology[4]).
Konsep
inti peradaban Barat adalah teori ilmu, wujud dan teori nilainya. Bagaimana
Barat memahami realitas dan kebenaran menurut sudut pandang mereka yang telah berevolusi
dari berbagai macam kepercayaan, tragedi dan trauma. Konsep ilmu itu-lah yang
menjadi basis pengembangan ilmu pengetahuan yang kemudian dikembangkan sesuai
dengan metode, dan standar ilmiah yang telah dibawa pada epistemologi sekuler.
Ilmu
Jiwa, yang dulunya mengkaji tentang jiwa berubah menjadi ilmu tentang gejala
jiwa (behavior). Ilmu Hayat, yang dulunya mempelajari tentang makhluk
hidup, kini menjadi ilmu yang dipelajari secara faktual-empirik belaka. Ilmu tentang
sejarah manusia, telah menyempit pada ilmu tentang tulang, alat-alat perburuan,
candi, arca dan lain-lain. Manusia, telah dipisahkan secara total, jiwa dari
raganya. Ilmu tentang politik dan pemerintahan, dihilangkan dari campur tangan otiritas
Tuhan. Kekuasaan diserahkan sepenuhnya pada manusia. Begitu pula, pada
masalah-masalah urusan rumah tangga (oikos-nomos), telah mengarah pada
kajian transaksi kapitalis-ribawi. Akhirnya, bersamaan dengan kemajuan penemuan,
sains dan teknologi, tragedi kemanusiaan juga semakin menjadi-jadi.
Apa yang disebut ‘perubahan’, ‘pembangunan’, dan ‘kemajuan’ dalam semua
aspeknya, dalam peradaban Barat, adalah hasil akhir dari pencarian tiada henti
dan perjalanan tanpa akhir yang didorong oleh keraguan dan ketegangan batin.
Konsep-konsep tentang perubahan, pembangunan, dan kemajuan selalu dipahami
dalam konteks kehidupan duniawi dan senantiasa menyajikan pandangan alam yang materialistic,
yang dapat disebut sebagai bentuk eksistensialisme humanistik.[5]
Meski
telah menjadi nyata, ratusan ribu Universitas telah mengembangkan konsep dan
epistemologi demikian, namun usaha untuk mengembalikan posisi ilmu, teori,
hukum, metode dan unsur-unsur filosofinya pada konstruksi keilmuwan masih bisa
diupayakan. Bahkan, islamisasi adalah solusi atas kesenjangan ilmu dengan realitas
kemanusiaan.
Ilmu
telah berpindah ke Barat. Sains, teknologi, hukum dan scientific tradition
telah bermigrasi dari dunia islam yang dikembangkan dengan tradisi yang tidak
lepas dari Qur’an dan Hadits menjadi bebas agama dan campur tangan Tuhan. Dan
jejak-jejak pemikiran serta sejarah itu masih ditayangkan kembali dalam tubuh
ilmu pengetahuan. Akhirnya ilmu pengetahuan menjadi problematis.
“Yang
penting kalian bisa menjawab soalnya dengan benar!”, kata seorang Dosen. Padahal,
ungkapan itu tidak harus berhenti sampai disitu. “Dan kalian menjadi lebih
beradab dan santun dengan mengetahui ilmu ini”. Sebab, hasil pemikiran dari
rahim Barat menjadikan ilmu pengetahuan kering makna, nilai dan spirit. Yang
ada hanya rasionalitas. Sementara dalam konsepsi dan pandangan hidup serta
budaya dalam dunia islam, tidaklah demikian. Dalam budaya masyarakat islam, etika
menjadi syarat utama dalam tradisi ilmu. Seseorang tidak akan diambil
haditsnya, jika ia ternyata adalah seorang pembohong, faasiq apalagi faajir.
Kualitas pembawa ilmu, dipengaruhi bagaimana kualitas ilmu yang ditanamkan kepada
para pembelajar.
Dalam
pandangan keilmuwan islam, fenomena alam tidaklah berdiri sendiri tanpa relasi
dan relevensinya dengan kuasa ilahi, karena, seperti dikatakan Muhammad Iqbal,
ia merupakan medan kreatifitas Tuhan sehingga mempelajari alam akan berarti
mempelajari dan mengenal dari dekat cara kerja Tuhan, di alam semesta.[6]
Oleh
karena itu, sangat mendesak bagi umat islam untuk membangkitkan kembali api
ilmu pengetahuan yang sempat menyala di abad keemasan islam. Api yang menerangi
Timur dan Barat. Dan menjadikan ibukota-ibukota Kekhilafahan Islam kiblat ilmu
pengetahuan. Kota kosmopolitan yang didalamnya, para intelektual, ilmuwan,
ulama, orang-orang shalih, ksatria pemberani serta pemimpin yang adil menjadi
tonggak peradaban.
Jihad
Intelektual
Persoalan
ilmu pengetahuan yang problematis seperti dijelaskan dimuka, memang belum
banyak diketahui oleh orang islam sendiri. Dari konsep ilmu sekuler tersebut, minimal
umat islam terbagi menjadi tiga. Pertama, mereka yang tidak perduli, dan
tetap menjalankan dan mengajarkanyadi berbagai lembaga pendidikan. Kedua,
mereka yang sadar namun pasrah dan tidak mengambil langkah apa pun. Ketiga,
mereka yang mengetahui, dan berjuang untuk menegakkan espistemologi ilmu yang
benar.
Bahkan
di kampus-kampus islam sendiri pun, masih banyak yang memilih dan tidak
menyadari akan pentingnya menegakkan bangunan keilmuwan berbasis konsep dan
epistemologi islam. Sehingga setiap kemajuan, peradaban dan perkembangan diatur
dalam konsepsi yang integratif dan komprehensif. Itulah yang seharusnya
dilakukan oleh para intelektual dan sarjanawan muslim. Berjihad dengan Ilmu.
Melawan konsep Ilmu Sekuler yang mewabah di berbagai institusi pendidikan.
Perjuangan itu, tidak lain adalah usaha untuk memurnikan (refinement) kembali
cara pandang (worldview), sistem keyakinan (beliefness system) yang
akan berwujud pada ucapan dan tingkah laku. Jihad itu adalah usaha untuk membangun
manusia berilmu dan beradab. Membersihkan debu-debu kepercayaan yang memuja dewa,
akal, dan penuh perwujudan mitologi dan paganisme kepada kepercayaan yang
membebaskan dari doktrin, dogma dan ilmu yang merusak fitrah Tauhid.
Berkaitan dengan kemajuan
dan perkembangan, Prof. al-Attas menyebutkan bahwa menurut faham islam, maka
perubahan dan perkembangan dan pembangunan merujuk kepada diri dan berarti pemulihan
kepada pemurnian asal ajaran agama serta tauladan orang dan masharakat islam
yang tulen; apabila terdapat keadaan di mana orang dan masharakat islam sudah
tersesat dan keliru dan jahil dan zalim kepada dirinya masing-masing, maka daya
usaha serta kegiatannya untuk mengarahkan dirinya ke jalan yang lurus dan benar
yang akan memulihkannya kepada keadaan keislaman yang sejati asli – itulah
pembangunan.[7]
Semua itu tidak lain
adalah karena sekularisasi ilmu. Yang menyebabkan pada tataran epistemologis, konsep
dan hirarki ilmu menjadi rusak. Ilmu alam disamakan derajatnya dengan ilmu
aqidah. Ilmu patung disamakan derajatnya dengan ilmu tafsir. Ilmu ekonomi riba
diangkat setara dengan ilmu syariah. Ilmu Seni mengalahkan ilmu akhlak. Dan
ilmu logika mengalahkan adab. Dan penyamarataan itu, berlangsung hampir
diseluruh institusi pendidikan di negeri muslim.
Oleh karena itu, islamisasi
bukan lagi seharusnya menjadi wacana. Sebab kebutuhan akan keberadaannya sangat
mendesak. Kebutuhan akan pembangunan kembali konstruk dan hirarki ilmu dalam
derajat dan maqom-nya yang benar. Sebagaimana diketahui, bahwa ilmu yang
paling tinggi, adalah ilmu tentang Allah[8]. Sehingga
ketika ilmu tersebut telah merasuk ke dalam jiwa, maka bencana ilmu pnegetahuan
bisa diatasi. Bencana ilmu itu adalah jika suatu disiplin ilmu tidak sesuai
dengan kehendak Allah dalam masalah agama, yaitu kehendak yang dicintai dan
diridhai-Nya. (Wallohu a’lam bi as-Showab)
[1]Abu Hasan
Ali an-Nadwy, Derita Dunia akibat Kemunduran Umat Islam, Jakarta:
Fadlindo, 2006, hlm. 301
[2] Marvin
Perry, Peradaban Barat; dari Zaman Kuno Hingga Zaman Pencerahan, Bantul:
Kreasi Wacana, 2012, hlm. v
[3]
R. D. K. Herman, Traditional knowledge in a time of crisis: climate change, culture
and communication, Jurnal Sustain Sci, (Vol. 10, No. 2, April 2015), hlm.
5-6
[4]
R. D. K. Herman, Traditional knowledge in a time of crisis: climate change,
culture and communication, hlm. 6
[5] SMN
al-Attas, Islam dan Sekulerisme,
Bandung: PIMPIN, 2010, hlm.173
[6] Mulyadhi
Kartanegara, Integrasi Ilmu; Sebuah Metode Holistik, Bandung: Mizan,
2005, hlm. 21
[7] SMN
al-Attas, Risalah Untuk Kaum Muslimin, Kuala Lumpur: ISTAC, 2001, hlm. 88-89.
[8]
Ibn Qayyim menyebutkan dalam al-Fawa’id, bahwa kemuliaan suatu disiplin ilmu
bergantung pada kemuliaan objeknya dan kadar kebutuhan manusia terhadap objek
tersebut. Ilmu yang seperti itu tidak lain adalah ilmu tentang Allah beserta
cabang-cabangnya. (Lihat: Ibn Qayyim, Fawaid
al-Fawa’id, Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2013, hlm. 353)



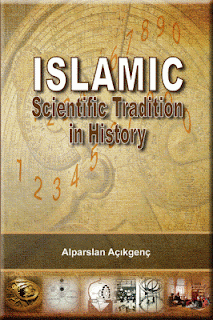


No comments:
Post a Comment